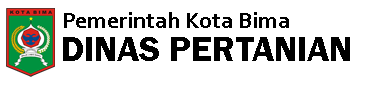Refleksi Kemerdekaan RI Ke-80 dalam Paradigma Pembangunan Pertanian di Kota Bima Provinsi NTB

Oleh: Dr. Wulandari
Dinas Pertanian Kota Bima
Pertanian merupakan sektor unggulan di NTB, menempati posisi penting dalam struktur ekonomi daerah. Kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berkisar antara 21–23 %. Menurut dokumen Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kota Bima Tahun 2024, disebutkan bahwa sektor pertanian (termasuk pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan) menyumbang total luas lahan sebesar 19.759,39 hektare (ha). Refleksi kemerdekaan tidak hanya simbol historis, melainkan janji kedaulatan, terutama kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Di Kota Bima dengan ekologi lahan sawah terbatas dan dominasi lahan kering, tantangan klasik produktivitas, iklim kering, akses modal-pasar, dan alih fungsi lahan menuntut pembaruan paradigma dari growth-centric menjadi people, climate, dan institution-centric, secara abstraksi sebagai berikut;
- Growth-Centric (Produksi-Sentris)
- Definisi: Paradigma lama yang menekankan peningkatan output produksi (tonase padi, jagung, kedelai) sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.
- Karakteristik: Fokus pada swasembada pangan nasional. Program top-down (instruksi tanam serentak, target produksi). Ukuran keberhasilan: peningkatan produktivitas & surplus.
- People-Centric (Berbasis Rakyat/Petani)
- Definisi: Menempatkan petani sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Ukuran keberhasilan dilihat dari peningkatan kapabilitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani.
- Karakteristik:
Pendekatan pemberdayaan: petani terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
⇒ Contoh implementasi:
- Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT): petani belajar bersama, bukan sekadar menerima teknologi dari penyuluh.
- Program Farmer Field School di Kota Bima untuk up-skill teknis budidaya yang meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial petani.
- Climate-Centric (Adaptif Iklim & Lingkungan)
- Definisi: Paradigma yang menekankan keberlanjutan ekologi, adaptasi perubahan iklim, dan mitigasi degradasi sumber daya alam.
- Karakteristik: Pertanian harus resilient terhadap perubahan iklim (kekeringan, banjir, hama baru). Fokus pada efisiensi air, konservasi tanah, varietas tahan iklim.
⇒ Contoh implementasi:
- Climate Smart Agriculture (CSA): varietas padi toleran kering di Kota Bima; penggunaan irigasi tetes untuk hortikultura (cabai, tomat).
- Penerapan rainwater harvesting (embung, sumur resapan, parit kontur) untuk mengatasi defisit air.
- Institution-Centric (Penguatan Kelembagaan & Tata Kelola)
- Definisi: Paradigma yang menekankan pentingnya kelembagaan petani, pasar, dan tata kelola kolaboratif (triple helix: pemerintah–akademisi–swasta + masyarakat).
- Karakteristik: Fokus pada aturan main, insentif, dan kelembagaan kolektif (kelompok tani, koperasi, P3A/GP3A irigasi).
Kinerja pertanian tidak diukur hanya produksi, tetapi juga keberlanjutan kelembagaan.
⇒ Contoh implementasi:
- Optimalisasi peran kelompok tani sebagai kelas belajar, unit ptoduksi dan wahana kerjasama.
- Kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) di Kota Bima untuk mengelola distribusi air irigasi secara adil.
Pemberdayaan & tata kelola kolaboratif mengarahkan penyuluhan bergeser dari transfer of technology ke dialog problem-posing (Freire, 1984) melalui Sekolah Lapang dan farmer field school yang menumbuhkan refleksi-aksi (praxis). Partisipasi bermakna: petani dilibatkan sejak diagnosis kebutuhan sampai evaluasi dampak; ukurannya bukan jumlah pelatihan, melainkan derajat agency dan pengaruh pada keputusan. Hal ini perlu dukungan stakeholder Triple helix plus (pemda–akademisi–bisnis + komunitas/finansial) mengorkestrasi inovasi, pembiayaan, dan pasar.
Sebagai Ruang Diskusi: Makna Kemerdekaan di Tingkat Lokal
Kemerdekaan RI ke-80 memanggil pergeseran kekuasaan pengetahuan dari birokrasi ke komunitas produsen. Penyuluhan pertanian dengan lensa Paulo Freire & Chambers mengubah paradigma keberhasilan pembangunan pertanian di Kota Bima bukan hanya tonase, melainkan kebebasan memilih strategi teknis budidaya, ketahanan terhadap guncangan iklim/ pasar, dan ruang tawar petani dalam rantai nilai. Keberlanjutan menjadi pagar etis untuk menghindari eksploitasi sumberdaya yang menumpuk risiko antar-generasi.
Di Kota Bima, ini berarti menutup kesenjangan air dan pasar, memandirikan pengetahuan, memperkuat kelembagaan, serta mengarusutamakan praktik adaptif-iklim. Dalam semangat kemerdekaan, paradigma ini menuntut adanya kesadaran kolektif bahwa pertanian adalah instrumen strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi lokal sekaligus kontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional.